Nurus Shalihin Djamra

TAUHID DAN KESHALEHAN SOSIAL;
Membumikan Tauhid Dan Meretas Pembebasan Bagi Mustadh’afin[1]
Oleh: Nurus Shalihin Djamra, M.Si[2]
Jika gagasan tentang Tuhan tidak memiliki keluwesan. Niscaya ia tidak akan mampu bertahan untuk menjadi gagasan besar umat manusia. Karena itu, setiap generasi harus menciptakan citra Tuhan yang sesuai dengan zamannya.
--Karen Armstrong, 1993—
Memantik makna tauhid sesungguhnya tidak tuntas pada titik mengetahui”what” dan ”how” segala hal tentang Tuhan. Jika dalam literatur klasik makna Tuhan sebagai poros dari Tauhid; di pancarkan melalui pemaknaa imajiner dari teks-teks agama, maka tauhid dalam ”tradisi” lisan dan mantik belum utuh menjadi hal yang sosial dan terhujam. Hari ini, Tauhid mesti dijadikan sebagai titik kulminasi semangat ketuhanan, dan di arahkan pada locus kemanusian. Inilah yang dikatakan sebagai ”tauhid sosial”. menukikkan hal ini, benarkah ada relasi aktif antara Tauhid dengan semangat ”liberasi”?
Tauhid berpijak pada fondasi kalimat ”la illah ha ilallah”. Ini merupakan nuclear of mean dari tauhid. Ada komitmen trasendental yang ditawajuhkan hanya kepada Allah swt. Hal ini diperkukuh secara implisit dari QS. QS. Adz-Dzariat (51):56, “telah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaKu.” Ayat ini kian mengariskan tapak kehidupan manusia bermuara kepada Tuhan. Namun demikian, walaupun muara kehidupan itu adalah tuhan, bukan berarti kehidupan kosong, kering, dan tidak diisi dengan aksi transformasi. Kehidupan tidak akan bermuara tanpa dikawal, didorong oleh kebajikan yang luwes terhadap alam. Dalam kerangka inilah sesungguhnya tauhid menemukan makna sejatinya sebagai the heart of islam (jantung islam), hingga menjadi amunisi, tumpuan spirit untuk melakukan transformasi—ujungnya adalah liberasi. Tauhid dalam tatanan praxis mesti menjadi komitmen keimanan terhadap Allah per se; keluar dari komitmen ini berarti keluar dari lingkaran tauhid, bahkan bisa dikatakan ”fasiq”. Nyata, dari komitmen ini setiap ”pemberhalaan” adalah kemapanan yang mesti dikuliti dan ditelanjangi dari kehidupan umat. Dalam locus inilah relasi tauhid dengan liberasi berkelidan. Kemudian seutuhnya tauhid menjadi dorongan berpijarnya ”keshalehan sosial”.
Dari Komitmen Transendental Ke Komitmen Sosial
Pada awalnya adalah tauhid an sich. Kini maknanya, merembes dan luwes menjadi tauhid sosial, yaitu dari komitmen hanya kepada Allah, lalu dihayati sebagai landasan gerakan untuk melakukan liberasi. Tepat jika tauhid sosial dipahami sebagai komitmen dan aktualisasi Islam dalam totalitas kehidupan masyarakat, dalam berituk amal salih sosial.
Jika dalam bentuk yang paling orthodoks, tauhid hanya baru dihayati dalam lintang vertikal, belum melintasi lintang horizontal, hingga tauhid masih berkutat, berpusar-pusar indah dalam dimensi privat, dan hanya memberikan impuls ”tenang” secara personal. Di balik tradisi ini, sesungguhnya tauhid memiliki multi dimensi, ruang luwes seperti rhizoma, yang menyentuh ruang-ruang sosial. Dalam bentuk ini, tauhid akan terasa hidup, membumi, dan mendatangkan eksternalitas positif bagi manusia secara universal dan yang paling bermakna tauhid menjadi dawai kolektif, yang membuat semua orang merasakan ekstase kebertuhanan yang membebaskan dan memerdekakan.
Tauhid dalam makna universal merupakan paradigma teologis yang bersifat memerdekakan atau membebaskan manusia. Ekses tauhid ialah membebaskan manusia dari rantai ”idolisme” serta memerdekan manusia dari ”kemapanan” yang menyesatkan. Tauhid merupakan komitmen menyeluruh, mendasar, menjadi darah bahwa sumber kehidupan adalah Allah, dan dimuarakan pada kemanusiaan.
Meminjam terma yang dikemukan oleh Amien Rais bahwa pandangan tauhid bertelekkan pada komitmen meng-esakan Tuhan (unity of Good head), serta melahirkan konsepsi ketauhidan yang lainnya dalam wujud keyakinan akan kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan pedoman hidup (unity of guidance), dan kesatuan tujuan hidup (unity of tbe purpose of life) umat manusia[3]. Kelidan kelima sudut pandang ini menjadikan tauhid terpencar-pecar sebagai energi baru untuk mengaktualkan semangat ”ketuhanan” dalam sistem sosial, hingga ruang publik sebagai refresentasi ruang sosial dilingkupi oleh semangat transendental.
Tauhid bukan sebuah ’diktum’ teologi per se, apalagi sebuah domain agama yang tegak melintang, tanpa dibaringkan secara horizontal. Tetapi tauhid sesungguhnya merupakan ’domain’ yang bermain dalam dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Dalam Lucus ini, semangat tauhid bersipat all-embracing bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik ekonomi dan budaya. Sebagai jantung dari agama Islam, tauhid mesti bertapak di bumi. Dalam bentuk inilah Islam mampu dicitrakan sebagai agama syumuliyah dan rahmatan lil alamin. Memperkukuh hal ini Kuntowijoyo mengutarakan bahwa tugas terbesar Islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai tauhid[4]. Jika kita menoleh kedalam ruang suci agama (baca: Al-Qur’an), maka ”kita” akan menemukan dorongan yang berserak untuk membumikan ”keimanan”, ”komitmen” tauhid. Karena itu, tepat jika Islam diartikan sebuah humanisme, yaitu agama yang sangat sentral mementingkan manusia sebagai tujuan sentral.
Mengaktualkan tauhid sebagai poros humanisme, berarti mengakui bahwa tauhid didorong ke arah emansipasi teologis yang diinduksi dari fitrah manusia sebagai khalifah serta mencoba memahami keluwesan fungsi manusia melebihi, melampaui fungsinya sebagai abdi tuhan an sich. Ketika manusia memahami esensi dirinya, maka tak ayal Ia akan mendapatkan sense of freedom dalam dirinya. Dalam maqam ini, seketika nilai kemerdekaan, pembebasan dari dominasi, hegemoni, baik oleh thaqut material, maupun thaqut immaterial mengental dalam diri seorang mukmin. Nurcholis Madjid dalam konteks ini membangun asumsi bahwa terdapat korelasi positif antara sikap bertauhid dengan nilai-nilai pribadi yang positif seperti iman yang benar, sikap kritis, penggunaan akal sehat atau sikap rasional, kemandirian, keterbukaan, kejujuran, sikap percaya pada diri sendiri, berani karena benar, serta kebebasan dan rasa tanggungjawab[5].
Kian terngiang, betapa tauhid mesti diorientasikan pada aras kolektif, tidak hanya dipakukan pada aras individual semata. Jika hal ini mampu ditransformasikan, maka tauhid akan menjadi amunisi, bangunan untuk membentuk keshalehan sosial. Dan tauhid dalam bentuk ini terasa, dilihat lebih hidup, segar, dan membebaskan. Karena memang kata Kuntowijoyo, tauhid harus diaktualisasikan: pusat keimanan Islam memang Tuhan, tetapi ujung aktualisasinya adalah manusia[6]. Dalam bentuk inilah, Islam menjadikan tauhid sebagai pusat dari semua orientasi nilai, dan pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dari transformasi nilai. Tertuang dari aras ini, dimensi tauhid berlimbak pada humanisme teosentrik; yang memusatkan diri pada keimanan terhadap Tuhan, dan mengarahkan perjuangan untuk kemulian peradaban manusia.
Tauhid; Benih Pembebasan Bagi Mustad’afhin
Tanpa disadari ”kita” tengah berenang dalam samudera modernitas yang saling bertumpuan dengan industrialisasi. Dalam era ini, logika kemanusian seketika digantikan oleh logika konsumerisme. Orientasi nilai ”transendental” perlahan ditutupi, dan nyaris tak terlihat oleh nilai-nilai pasar-isme. Dalam bentuk ini, agama cenderung dihayati secara simplistis; karena memang dalam era modernitas segala hal sedang terseret arus deras rasionalisme pasar, hingga agama hanya mampu menjadi apresiasi umum, dan konsumsi publik, hingga bertekuk dalam komiditas politis. Agama dalam bentuk ini nyaris kehilangan eksistensialitasnya yang originil; agama tak lagi menjadi semangat pembebasan. Alhasil, bergelimpangnya ”ketertindasan” kaum musthad’afin oleh modernitas adalah directly impulse dari keberagamaan yang kian berlari meninggalkan tapal humanisme teosentriknya.
Menyahuti ini, tidak mengherankan jika Nietzche membakar jengot kaum spritualis, agamis dengan pernyataannya ”tuhan telah mati”. Namun pernyataan Nietzche ini bukan berkonotasi atheis, yang menegaskan dirinya anti-tuhan. Tapi sesungguhnya ini merupakan sentilan ketika agama telah menjadi kemapanan akut. Teologi kematian Tuhan ala Nietzche ini bermakna bahwa agama kini tidak lebih sekedar ilusi belaka. Intinya, penegasan bahwa kepercayaan akan adanya Tuhan dan seluruh aspek kehidupan yang dikaitkan dengan kepercayaan tersebut tidak lagi menjadi pilihan mutlak[7]. Patronase terhadap Tuhan-Tuhan digital telah mengantikan ”tauhid”; kekuasaan metafisik, tertindih oleh kekuasaan cyberspace. Kini, orientasi nilai melampaui nilai transendental religius , dan terjerembab pada lingkaran nilai virtualitas. Agama kini berhamburan masuk perangkap pencitraan ekslusifisme, hingga ini menjadi peneguhan atas politik identitas berbasis agama dan tak terbendung lagi.
Kini agama sedang beranjak, beralih kedalam keranjang modernitas; yaitu modernitas yang sama sekali menegasikan, menyintas nilai-nilai universalitas. Ironisnya, agama diperlakukan oleh pemeluknya ”sekeder” mitos, hingga tak lagi berdampak untuk menyegarkan, menenangkan, dan tidak lagi mampu membakar semangat membebaskan dari kemapanan. Saung agama telah mulai reot, karena memang agama kini terputus dari siklis transformasi. Sebab agama sedang berada dalam dunia sedang diredung malapetaka kemanusiaan. Proyek dehumanisasi, menyelubungi kehidupan manusia. Realitas sosial, bahkan agama kian terjebak pada kemapanan hebat. ”Kita” sedang mendiami kavling kemapanan yang saling berhadapan-hadapan dengan ”ketertindasan”. Antara kemapanan dan ketertindasan hampir tidak ada lagi ”jedah”, ”spasi”, ”ruang”—kedua-dua yang saling mengisi realitas. Namun, diujung ”permainan” ketertindasan tetap menguratkan luka mendalam dibawah kelangengan kemapanan. Inilah era, di mana raungan musthad’afin memecah kesenyapan alam, mengiris hati yang rapuh.
Melampaui nestapa kemanusian ini, betapapun manusia lari menjauhi Islam. Namun tetaplah dalam struktur Islam yang nyaris tak terlihat, menyimpan ”segudang’ kekuatan. Kekuatan ini jika ditransformasikan akan menjadi ”atom” pemicu mendobrak, mejungkalkan kemapanan. Kuntowijoyo amat paham bahwa dalam Islam, tauhid mempunyai kekuatan membentuk struktur yang dalam[8]. Struktur ini berlapis dan memiliki kesatuan, hingga jika dihidupkan seketika menjadi medan yang membebaskan bagi kemapanan.
Ada sebuah konsesus primodial dalam masyarakat Islam, yaitu bahwa Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam[9]. Inilah sesungguhnya yang menjadi pijakan bahwa satu muslim terhadap muslim yang lain merupakan pembebas, penjaga bagi muslim yang lainnya. Mereka bak satu tubuh yang saling mengisi, menguatkan. Karenanya, untuk memperkokoh konsesus ini, tauhid terhujam sebagai semangat ketuhanan sekaligus kemanusian. Di ujung yang lain, tauhid pembebasan tidak hanya menusuk ke dalam organ masyarakat Islam, tetapi juga mesti dilayangkan keluar masyarakat Islam, untuk membebaskan ”Mereka” yang menjadi korban dominasi dari kemapanan.
Secara historis, Islam hadir dengan kekuatan tauhidnya di tengah-tengah masyarakat mapan. Kemudian, Islam mampu merasuki kelompok ”pinggiran”, ”tertindas” oleh kemapanan itu. Waktu demi waktu Islam dengan kekuatan yang membebaskan mampu membuat kelompok mapan terperangah, dan akhirnya bertekuk lutut dan merebahkan diri dengan sekelumit ”keimanan” terhadap Allah. Ini adalah fakta historis, yang tak akan terbantahkan bahwa Islam teguh, kuat dengan tauhid pembebasan.
Kilas balik; sejarah awal Islam yang disampaikan oleh Muhammad saw, ternyata menyimpan pernik-pernik tauhid pembebasan, hingga tak selang berapa lama Islam mampu menciptakan tatanan sosial yang egaliter. Islam sendiri pada awal perkembangannya banyak dipeluk oleh orang-orang yang bukan merupakan golongan elit di masyarakat. Muhammad sebagai pembawa risalah juga berasal dari keluarga Quraisy yang walaupun cukup terpandang, tidak tergolong sebagai keluarga yang kaya dan memiliki status social yang tinggi. Pada saat itu Islam menjadi tantangan yang membahayakan para saudagar kaya Mekah, sehingga kemudian mereka menolak ajarannya. Bukan semata-mata karena mereka menolak risalah tauhid, tetapi lebih kepada ketakutan mereka terhadap Islam yang akan membawa perubahan sosial, khususnya pada tingkatan kekuasaan, baik politik maupun ekonomi. Dalam konteks inilah, tauhid menjadi poros dimana semangat pembebasan tetap berdesing. Dan dalam locus ini jua, tauhid menjadi pengerak keshalehan sosial dalam masyarakat Islam.▪
[1] Makalah ini ditulis dalam rangka pengantar Diskusi di LK II- HMI Cabang Bukittinggi, 5-11 Januari 2009, Bukittinggi.
[2] Penulis adalah Direktur Litbang Nagari Institute, dan Dosen IAIN Imam Bonjol, Mantan Ketua HMI Komisariat Syari’ah periode
[3] Dr. Haedar Nashir , MSi, Prespektif tauhid Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam www. muhamdiyah.or.id
[4] Kuntowijoyo, Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), h. 167
[7] Lihat dalam Bryan S. Turner, Agama dan Teori Sosial, (Yogyakarta: IRCiSoDM 2006), h. 72
[9] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

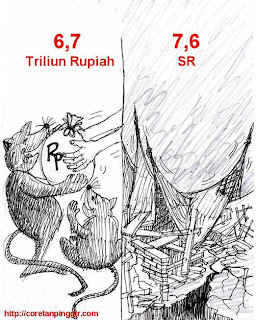
Komentar