Gemercik Api dari Dua Kutub yang Beradu
Judul : Api Paderi
Penulis : Muhammad Sholihin
Penerbit : Narasi
Cetak : Februari 2010
Tebal : 215 Halaman
Penulis : Muhammad Sholihin
Penerbit : Narasi
Cetak : Februari 2010
Tebal : 215 Halaman
Peresensi : Abdullah Khusairi*
DUA KUTUB. Dimana pun itu ada. Termasuk dalam agama dan budaya. Kinipun terjadi begitu, pro kontra Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) adalah dua kutub yang beradu. Kutub yang sulit bertemu. Karenanya, membaca mempelajari dua kutub dan mempertemukannya kadang menjadi sia-sia jika tidak dari sudut yang pas.
Buku ini, lahir dari seorang penulis muda asal Ranahminang yang mengaku baru masuk ranah sastra. Ia berhasil menjalin dua kutub tersebut dalam sebuah cerita. Penulis novel ini berani menulis novel setelah tunak di Jogja sana. Novel lahir setelah ia jauh dari objek yang dituliskannya.
Begitulah, akhirnya, setting tempo doeloe Nagari Paninjauan di pinggang gunung menjadi bagian penting dari narasi yang terbangun. Lalu dengan "memanfaatkan" perdebatan dua kutub antara kaum paderi dengan kaum adat, penulis novel ini menghadirkan kisah-kisah lama dengan baik.
Perseteruan kaum paderi dengan kaum adat sudah menjadi cerita baik dalam khazanah pemikiran Islam modern, sejarah pra kemerdekaan, maupun sejarah Islam secara umum. Cerita heroik ini berawal dari pembaruan di Ranahminang dengan masuknya gerakan Wahabi.
Cerita heroik Harimau Nan Salapan dalam gerakan pemurnian Islam sebuah episode sejarah yang melekat dan memiliki hubung kait dengan titik prakemerdekaan. Ada tumbuh semangat perlawanan untuk lebih maju dan memerdekakan diri dari kungkungan kemapanan. Di sinilah, jika kita merenunginya, seakan-akan mustahil, Tuanku Nan Renceh dari Kamang Bukitinggi yang begitu teganya membunuh "eteknya" sendiri, karena tidak mau berhenti dari mengunyah sirih. Begitulah kerasnya “perang” terhadap Takhayul Bid'ah dan Churafat (TBC) di Ranahminang menjadi sebuah gerakan yang menimbulkan konflik panas. Memercik api.
Serpihan sejarah Kaum Paderi dengan balutan romantika, konflik, adat, budaya, agama, paling tidak mengingatkan kita bahwa hidup memang selalu berpagut pada cara pandang terhadap kehidupan. Keyakinan dan kenyataan selalu berhubung kait.
Tokoh Datuk Sati dengan para parewanya, ayam aduan bernama Gegar Jalu, menerangkan sudah menjadi budaya sejak saisuak hal-hal yang mau dimurnikan oleh gerakan Orang Asing. Walaupun begitu, ia sangat moderat terhadap hal baru. Lain lagi dengan Datuak Tan Kuniang, yang tak bisa diasak pendapatnya. Diasak layu, dianjak mati! Sementara, Tenku Hudzail dari sisi lain, yang membawa "sesuatu" dari rantau agaknya harus mendapat masalah. Begitulah, awalnya lalu ada romantika adik si Midin, Puti Jalito membuat lini cerita berkelindan dengan dinaungi narasi nagari yang indah. Paninjauan.
Ada masalah teknis pada beberapa bagian bangunan kalimat dan istilah dalam novel ini. Paling tidak sedikit mengganggu. Dan mesti direkomendasi kepada penulis dan penerbit untuk kembali mengoreksi. Walau akan menjadi alasan, sebuah remah-remah sejarah ini sudah masuk wilayah fiksi, hal ini kadang tetap menjadi ganjil dan mustahil di pikiran pembaca di ranah sendiri. Dan itu, sangatlah mungkin bagi pembaca untuk komplain jika melihat kenyataan yang ada dengan diceritakan dalam novel. Atau paling gawat, jika fiksi ini hanya satu-satunya sumber bacaan di masa depan nantinya tentang pertikaian kaum tua dan kaum muda. Maka alamat novel ini menjadi tambo! Apalagi bagi Ranahminang, tempat dimana setting cerita itu berada dan segala sesuatunya sangat banyak yang tahu tentang apa yang diceritakan tersebut.
Badiak, Cenayang (Clairvoyance), adalah dua kata yang paling mungkin "dicurigai" menyaru secara sah dalam novel ini. Alasannya, ini bahasa dari ranah yang lain. Bagi penulis tentulah punya alasan tersendiri, namun "kecurigaan" akan kuat terasa ketika masuk lebih jauh. Dimana, ada komparasi ala penulis dalam cerita ke ranah Jawa. Misalnya, persis Tapa Brata Nyi Camara di Pantai Selatan (hal. 16). Komparasi ini terjadi di beberapa kali, seakan-akan penulis ingin menjelas lebih jauh tentang duduk persoalan. Sementara, persoalan baru muncul di benak pembaca, bagaimana jika pembaca tidak kenal dengan amsal yang jadi bahan komparasi itu? Ini bisa berbahaya. Inilah jika menulis cerita dengan setting sejarah.
Secara menyeluruh novel ini harus diapresiasi tinggi di ranah sendiri. Sebuah novel baru, penulis yang mengaku baru, perlu dibaca bagi siapa saja. Kenapa demikian, sebab penulisnya telah mencerita hal-hal lama dengan posisi dan persepsi yang baru dan segar. Memperkenalkan dua kutub pemikiran yang pernah ada dan mungkin masih "bertempur" di kepala orang-orang di sini. "Di negeri orang-orang pintar," menurut Makmur Hendrik.
Novel Api Paderi diyakini menjadi sebuah novel yang kuat, karena kekuatannya terletak pada narasi-narasi yang hidup dengan pendekatan kata-kata sastra. Lebih-lebih jika menceritakan suasana Paninjauan yang indah. Dua gunung, malam purnama penuh. Sawah. Angin sepoi-sepoi dan seterusnya. Memancing untuk pengambilan gambar untuk dijadikan film. Dan ini paling tidak, merekomendasikan para sineas untuk mengangkat novel ini ke skenario film.
Terakhir, dua kutub itu selalu ada sebagai kenyataan dalam kehidupan. Ia laksana dua rel yang diperlukan walau tak bisa dipertemukan. Dan memang tidak perlu dipertemukan demi keseimbangan. Selalu, “pertentangan dan perimbangan” memang ranum (hal.11) jika diusik oleh kepentingan yang menyaru ke dalamnya. Kepentingan tersebut berupa kekuasaan; ekonomi, daerah, juga kadang perempuan! Begitulah, novel ini hadir menjadi bukan sekedar sebuah cerita lepas. Ia memiliki sesuatu yang amat penting diceritakan untuk diambil sebagai i’tibar![]
*Abdullah Khusairi
Dosen Pemikiran Islam Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang


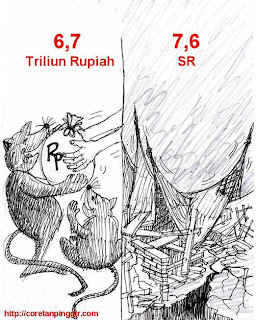
Komentar