TEOLOGI PLURALISME AHMAD WAHIB

Oleh: Muhammad Sholihin
Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis, aku bukan Buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin melihat orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya, termasuk serta dari aliran apa saya berangkat,
(Ahmad Wahib, 1981)—Pergolakan Pemikiran Islam.
Akar pluralisme di Indonesia telah ada sejak sejarah bangsa Indonesia ditegakkan. Uniknya, pluralisme di nusantara tak bersipat kaku; ia terus tumbuh dan berkembang menciptakan nilai-nilai baru yang kemudian membentuk gugusan multikulturalisme. Latar belakang terjadinya pluralisme dan multikulturalisme di Nusantara, merupakan sejarah panjang terbentuknya keindonesiaan. Gambaran ini terlihat secara detail lewat berbagai “persentuhan” budaya pada masa prasejarah. Temuan-temuan fosil dari lapisan plestosen bawah di Sangiran, misalnya, secara fisik sudah menunjukkan ciri yang variatif. Begitu pun jenis dan bahan peralatan yang digunakan. Kompleksitas masyarakat juga tampak di bidang sosial. “Salah satu keragaman budaya yang paling menonjol pada bahasa, yang merupakan perkembangan lanjut dari bahasa awal, Austronesia. Kemunculan penutur Austronesia dan budayanya di kepulauan Nusantara merupakan etnogenesis bangsa Indonesia, sekaligus peletak dasar budaya bangsa Indonesia.” Jelaslah, pluralisme bukanlah diskursus yang baru lahir di Indonesia. pluralisme ada sebagai artefak pluralitas budaya di Indonesia dan secara mengesankan ‘pluralisme’ telah dipraktekkan sebagai sebuah keniscayaan. Pluralisme yang diproduksi dari realitas pluralitas bangsa telah menjadi inspirasi struktur ber-negara, ideologi bangsa Indonesia, seperti halnya Pancasila. Singkat kata, tak ada celah untuk menolak pluralisme dalam tubuh bangsa Indonesia.
Perkembangan Indonesia sebagai entitas yang majemuk, ternyata tak berkembang linier sesuai dengan khittah awal didirikannya Negara ini. Dalam sejarahnya pergulatan ideologi, peneguhan primodialitas telah menyeret bangsa Indonesia kepada pertentangan paham, dan perspektif ber-negara dan ber-bangsa yang amat manifest dan mengkhawatirkan; berbagai pemberontakan yang digerakan oleh pemahaman agama secara parochial, seperti DII/TII—telah membuat kehidupan sosial-keagamaan kian terusik. Bahayanya, pluralisme tak lagi dianggap sebagai kebudayaan bangsa.
Pada era 69-an, saat bangsa digerogoti oleh political of nemesis. Di mana ideologi ber-agama, ideologi politik telah berubah menjadi mesin perang yang amat menakutkan—pada saat inilah lahir manusia baru; yaitu generasi muda, seperti Ahmad Wahib, Soe Hok Gie yang senantiasa mentafakuri bangsanya setiap saat lewat tulisan, dan kritikkan yang membuat merah telingga ‘mereka’ yang mengotori kehidupan ber-agama dan berbangsa saat itu.
Sikap spontan yang mengalir dari sosok seperti Ahmad Wahib ialah betapa kita butuh akan pluralisme, agar kita tak rapuh dikuras pertentangan, dan dendam, kebencian yang menistakan bangsa Indonesia sendiri. Perang melawan penjajah, perang melawan bangsa sendiri karena perebutan kekuasaan telah membuat Ahmad Wahib khawatir. Namun yang Lebih mengkhawatirkan bagi Ahmad Wahib ialah sikap penakut, sikap malas berpikir kritis atau kemapanan ber-agama. Hingga kondisi menjadikan Ahmad Wahib sebagai sosok manusia liar, progresif, dan pembaharu yang mengebu-gebu.
Pada era 60-an, polarisasi ideologi politik, agama telah membuat Ahmad Wahib menjadi muslim yang mereka-reka di posisi manakah sesungguhnya dirinya berada? Ia amat berhasrat menentukan posisi ideologi Islam di tengah lautan ideologi pada era itu. Hasrat ini membuatnya menjadi pemuda yang terus mencari inspirasi pemikiran, “aku benci homogenitas dan suasana monoton. Aku ingin mencari lingkungan baru yang masih kaya akan inspirasi”, demikian tumpahan perasaan yang digoreskannya di catatan hariannnya.
Dipenghujung hidupnya, Ahmad Wahib hanya ingin semua orang mau menerima dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya (absolute entity). Luapan pluralisme telah memenuhi rongga lehernya hingga membentuk artefak sikap merdeka dan tidak jumud dalam dirinya. Ahmad wahib hanya ingin mengajak umat Islam agar bersikap inklusif, tidak terpenjara oleh sikap orthodoksi ber-pikir yang tak menghasilkan apa-apa kecuali petuah kiai yang lusuh karena diulang setiap harinya. Bagi Ahmad Wahib “cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Al-Qur’an dan lain-lain sebagaimana terhadap pancasila harus berubah, yaitu dari sikap sebagai insan otoriter menjadi sikap insan yang merdeka, yaitu insan yang produktif, analitis, dan kritis.”
Teologi Pluralisme ala Wahib
Dalam bentuk apa teologi pluralisme Ahmad Wahib? Teologi sebagaimana yang jamak dipahami oleh kelompok konservatife, hanya sebagai sebuah ilmu tentang tuhan; di dalamnya hanya membicarakan sipat 20, sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Teologi dalam bentuk ini terasa kering dan tak mampu menyentuh realitas. Sesungguhnya yang lebih utama adalah bagaimana sifat Tuhan semestinya mampu dihayati dalam kehidupan sosial, hingga mampu melahirkan format ketauhidan yang membumi tak melangit. Demikianlah metode ber-teologi secara kontekstual; teologi yang senantiasa lahir, teologi yang mampu melakukan koreksi secara argumentatif berbasis nashiyyah, dan manqhulat terhadap pemahaman dan amaliyah beragama.
Teologi salafy, tak lagi mampu menjadi pemahaman tauhid yang memberikan ruang bagi keragaman pemahaman ber-agama. Kenyataannya, negasifisme menjadi jiwa pergerakan, jiwa dalam pemikiran ber-agama dewasa ini. Ironisnya, negasifisme imanen dalam tindakan ber-agama, penghakiman terhadap orang lain (the others), seperti kasus Monas, kasus Ahmadiyah—telah merusak tatanan beragama dewasa ini. Justru itu, perlu menegaskan kembali konsep pluralisme yang ditawarkan Wahib sebagai sebuah lintasan tauhid yang mampu memandang manusia dalam bentuknya yang sesungguhnya (absolute entity).
Memandang manusia dalam bentuknya yang paling alami, tanpa perlu mengait-gaitkannya dengan asal agama, kelompok apa—adalah inti teologi pluralisme Ahmad Wahib. Pandangan ini menemukan bentuk yang paling otentik dalam beberapa guratan ayat Al-Qur’an. Dan sesungguhnya Ahmad Wahib telah mencoba merenungkan Al-Qur’an secara afirmatif dalam kelompok diskusi terbatas, baik ketika beliau masih di Yogyakarta, maupun ketika berada di Jakarta. Hingga Wahib amat sadar betapa keesaan Tuhan (Allah swt) bukan berarti menafikan entitas pluralitas di luar selain Allah swt.
Sebagaimana halnya dengan Gamal Al-Banna seorang aktivis ikhwanul muslimin yang telah mencari pendasaran pluralisme pada Islam sebagai agama tauhid (kesatuan), sebab sebagian orang Islam cenderung menyangka bahwa tauhid sekaligus juga include dengan segala sesuatu yang ada di luar keesaan Tuhan. Segala yang berbau Islam lantas menjadi satu warna, seperti masyarakat Islam, sistem sosial Islam, Seni Islam dan seterusnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang di luar ajaran Islam kemudian dilarang. Maka Ahmad Wahib pun dengan logika yang sama merumuskan bahwa Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis, aku bukan Buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin melihat orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya, termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Sederhananya, bagi wahib dalam ber-agama, dalam ber-tauhid perlu bersikap terbuka dan tidak bernaung dalam fanatisisme ber-agama.
Tauhid mengandung makna “kesakralan Allah”, hingga haram melukiskan Allah dalam bentuk patung, dan menyamakannya dengan sesuatu yang berada diluar dirinya. Namun demikian, konsep ketauhidan dalam Islam meniscayakan pluralitas selain Dia (Tuhan Yang Maha Esa). Konsep tauhid dimaksudkan sebagai ajektif untuk Allah semata. Melekatkan ajektif ini kepada selain Allah merupakan usaha yang tidak dibolehkan karena akan menjerumuskan pada bentuk kemusyrikan. Kata Laa Ilaha Ilallah (tiada tuhan selain Allah) menggambarkan bahwa eksistensi Allah sangat pasti, dan pada waktu yang sama, menegasikan eksistensi selain Dia. Artinya, segala sesuatu selain dia (alam, manusia, dan sebagainya) bersifat pluralistik. Pluralitas di sini merupakan doktrin aksiomatis dari keesaan Tuhan. Hal ini tergambar dalam beberapa ayat al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, yang terdiri dari suku, bangsa dan budaya bahkan agama yang berbeda-beda. Dalam kerangka inilah, tauhid mempunyai dua dimensi. Satu sisi tauhid merupakan sakralisasi terhadap Allah swt, karenanya tak boleh ada kemusyrikan. Di ujung yang lain, tauhid juga merupakan sebuah komitmen untuk menerima keniscayaan pluralitas yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa ciptaannya lemah dan harus tetap berada dalam sikap keterbukaan dan kemauan untuk saling menopang satu terhadap yang lainnya.
Dalam kerangka teologi inilah Wahib berani mengurai pentingnya melihat manusia dalam absolute entity. Persoalannya bertumpu pada bahwa tak ada gunanya dalam melakukan interaksi sosial—sakralisasi terhadap sesuatu yang diluar Allah diterapkan, termasuk dalam aspek pemikiran keagamaan; semestinya setiap kelompok memberi ruang bagi ideologi/filosofi ber-agama selainnya ideologi kelompoknya. Cita-cita tertinggi Ahmad Wahib adalah terbentuknya tatanan ber-agama yang inklusif yang tetap bernaung dalam nilai utama nation-state.
Dan Sekretaris Eksekutif Nagari Institute

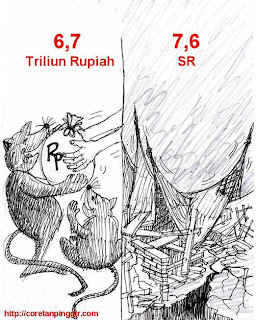
Komentar