NAGARI DAN EKSPERIMENTUM DEMOKRASI LOKAL

Implementasi UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah melahirkan spirit baru bagi masyarakat Minangkabau untuk mencari jati diri pemerintahannya dan kembali ke nagari adalah bukti nyata dari kehausan akan jati diri tersebut. Pencarian ini menjadi keniscayaan dari implementasi dari UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang telah memporak perandakan sistem demokrasi lokal di Minangkabau. Dengan hujaman politik ‘uniformisasi’—pemerintahan desa telah membuat dinamika di tingkat grass root berubah dengan drastis. Faktanya ‘demokrasi’ yang lahir dari desa-desa di Minangkabau mulai terdistorsi dengan intrik kekuasaan dan nyaris ‘demokrasi’ lokal berakhir dengan tragis. Karena lembaga-lembaga kultural di tingkat desa tidak lagi berfungsi semestinya. Inilah potret, bagaimana institusi demokrasi lokal dihabisi secara kontra-evolusi oleh sebuah rezim.
Namun, gerakan otonomi daerah yang menyapu pelosok nusantara telah membuat formasi struktur di daerah berubah kian cepat. Maklum, tidak ada satu pun entitas manusia Indonesia yang mau hidup secara sentralistik dan hidup dengan proses mengalir secara terbalik dalam kanal mono sirkuler dari daerah ke pusat. Gerakan otonomi daerah mendorong daerah-daerah melepaskan identitas mereka dari belitan pemerintah pusat. Dengan bentuk ‘kemandirian’ baru, baik mandiri dari segi ekonomi dan pembangunan—membuat daerah tumbuh dan berkembang sesuai dengan konstelasi di tingkat grass root. Ekspresi kemandirian ini, berarti sebuah pencarian jati diri baru bagi gerakan daerah dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan daerah.
Di Sumatera Barat sendiri, gerakan otonomi daerah memicu pencarian identitas baru. Dan gerakan ‘kembali ke nagari’ merupakan salah satu bentuk dari pencarian identitas tersebut--setelah UU No 5 tahun 1979 memporak-perandakan kehidupan di tingkat grass root di Minangkabau. Gerakan kembali ke nagari yang gencar dilakukan di Sumatera Barat pada dekade 1999 sampai sekarang masih belum tuntas dan proses pencarian ini terus mengalami sublimasi di tingkat elit, baik elit pemerintah, akademisi, praktisi sosial, dan elit-elit adat. Maka konstelasi pencarian ini menuai polemik ‘paradigma’ yang tak kunjung tuntas.
Nagari sebagai satuan adminitrasi dan kultural di Minangkabau, setelah UU otonomi daerah No. 22/1999 mencuat, wacana ‘nagari’ kembali menguat. Namun, tidak hanya sekedar wacana, pemerintah membuktikan kesunguhannya untuk kembali merebut identitas tersebut. Maka lahir lah Perda kembali ke Nagari No. 13/2000. Dengan Perda kembali ke ‘nagari’ ini, puing-puing bekas pemerintahan desa dibersihkan dengan memompakan kembali udara ‘demokrasi’ lokal. Lembaga-lembaga kultural yang menjadi soko demokrasi lokal, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM), kembali mendapatkan peran signifikan dalam kancah kehidupan ber-nagari. Kedua lembaga ini memiliki kerja yang independent dan memiliki legitimasi dari massa masyarakat. Perda No. 13/2000 ini membuat institusi nagari saat ini lebih berbeda dengan institusi nagari purba dahulu. Dalam Perda No. 13 tahun 2000 ini diatur tentang perlunya dibentuk BPRN (Badan perwakilan anak nagari), mirip dewan legislatif-nya negara—dengan BPRN ini, nagari diharapkan mampu menjadi institusi pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang bercorak modern. Ini lah bedanya ‘nagari’ purba dengan ‘nagari’ saat ini.
Nagari: Diantara Dua Polemik
Gerakan Kembali ke nagari, bukan hanya sekedar kembali dan berimajinasi, bagaimana ‘nagari’ purba dahulu dijalankan. Tapi, kembali berarti menuju nagari dalam bentuk baru namun tak tercerabut dari nilai-nilai sejarahnya. Karena bagaimana pun sejarah dan betuk kehidupan selalu berubah. Maka-nya ‘nagari’ hari ini berada pada persimpangan jalan. Akankah nagari diformat ulang atau malah mendandani nagari dengan baju lamanya dahulu? Dalam locus inilah, kegamangan gerakan kembali ke nagari membatu di masyarakat Minangkabau hari ini.
Ada dua bentuk kegamangan ber-nagari yang mendera masyarakat Minangkabau hari ini. Pertama, dalam imajinasi golongan elit Minang, mulai dari pemerintah, akademisi dan perantau—mencoba menjadikan institusi ‘nagari’ sebagai institusi modern. Dengan konstruksi struktur pemerintahan nagari yang berbasis modern, seperti, urgensi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di samping itu kelompok ini berupaya melakukan modernisasi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan nagari—dengan ini, berarti Nagari diseret dalam format yang sama sekali baru. Sementara golongan kedua. Tetap komitmen dengan bentuk ‘nagari’ purba dahulu, dimana peran datuk sebagai kepala suku tetap dipertahankan dalam membangun perintahan nagari. Golongan ini mencoba berimajinasi dan melalang buana pada kehidupan ‘nagari’ masa silam. Walhasil, ber-nagari hari ini berkutat dalam dua imajinasi. Hingga gerakan kembali ke nagari di Sumatera Barat saat ini masih berada dalam proses pencarian sintesis dari kedua kelompok ini.
Polemik kembali bernagari masih sebatas perdebatan tentang paradigma bernagari. Dan hasilnya kehidupan bernagari hari ini hanya sebatas eksperimen dan keberhasilan implementasi gerakan kembali ke ‘nagari’ ditentukan sepenuhnya oleh eksperimen paradigma yang memiliki pangkal argumen yang mengakar dan diperas dari sari pati ‘public reason’ yang ada di tingkat grass root. Kembali ke nagari adalah gerakan yang lahir dari kesadaran akan pentingnya ‘identitas kultural’ yang akan mengarahkan pemerintahan. Karena itu, gerakan kembali ke nagari sudah semestinya melibatkan semua pihak, bukan hanya kelompok elit di Minangkabau. Tapi bagaimana melahirkan sistesis ‘nagari’ yang berasal dari bawah. Hingga ‘nagari’ dapat dikatakan sebagai produk kultural bukan malah produk kekuasaan.
Kembali Ke Nagari dan Eksperimen Demokrasi Lokal
Zaman boleh berubah, tapi akar dari perubahan zaman tidak boleh tercerabut. Nilai-nilai demokrasi yang membentuk kehidupan nagari sama sekali patut dilembagakan secara rapi. Hingga kalimat ‘demokrasi’ yang berasal dari ajaran datuk Perpatih Nan Sabatang tetap menjadi ekspresi dan perilaku masyarakat Minang dalam kehidupan ber-nagari hari ini. Tapi, globalisasi telah terlalu jauh masuk dalam masyarakat Minangkabau. Maka dalam tata pergaulan masyarakat Minangkabau, gaya demokrasi pun mulai berubah dari basis kultural menjadi demokrasi intra kultural. Dalam arus globalisasi ini, demokrasi seperti apa yang pantas dilembagakan di Minangkabau hari ini? Demokrasi sesuai dengan konsep-nya memiliki makna gradual. Ada demokrasi yang diartikan sebagai demokrasi prosedural yang menekankan ‘bagaimana’ pemerintahan dibentuk dengan cara-cara ‘fairness”. Dan demokrasi juga bermakna sebagai ‘ajaran universal’ yang mengedepankan nilai-nilai kesamaan, keterbukaan, dan toleransi. Persis dengan ‘negara madinah’ yang digubah oleh Nabi Muhammad saw, di mana nilai-nilai demokrasi kultural secara alamiah membentuk sikap masyarakat Madinah dalam mengekspresikan kehidupan bernegara.
Sebenarnya, globalisasi sama sekali bukanlah musuh bagi demokrasi lokal di mana pun, termasuk di Minangkabau. Dengan globalisasi berarti demokrasi lokal akan semangkin kaya dengan nilai-nilai universal yang sangat mungkin diadopsi dan kemudian dipraktekkan dalam perilaku ber-nagari di Minangkabau. Kondisi ini, menuntut perlunya ‘eksperimen’ pemikiran tentang demokrasi lokal. Hal ini, mengingat demokrasi adalah sesuatu yang lahir dari interaksi nilai-nilai yang tumbuh secara periodik dan pada akhirnya membentuk bangunan ‘politik’ bagi sebuah struktur. David Held menilai eksperimen demokrasi sebagai sarana argumen yang mencuat dari “raison d’etre” tradisi yang saling berkelidan. Hingga eksperimen ini berfungsi sebagai kekuatan yang akan membentuk demokrasi yang genuine dan diterima sebagai sebuah kenyataan kultural dari tradisi.
Eksperimen demokrasi lokal berbarengan dengan momentum gerakan kembali ke nagari terasa kian penting. Sebab masyarakat Sumatera Barat hari ini tidak hanya bersipat homogen. Karena Minangkabau hari ini telah dibentuk oleh berbagai etnis yang timbul dari proses globalisasi yang masuk ke ranah Minang, seperti adanya daerah transmigrasi di wilayah Dharmasraya. Dengan kondisi ini, kompleksitas ‘nagari’ Minang semangkin membutuhkan eksperimen demokrasi yang lebih intens. Dalam prakteknya etnis jawa di Minangkabau memiliki sensitifitas demokrasi yang relatif berbeda dibanding etnis Minang. Hingga untuk menjadikan etnis jawa sebagai bagian dari unit ‘nagari’ diperlukan pendekatan kultural, agar pelembagaan demokrasi akan membuahkan perilaku yang mengakar dan akhirnya bermuara pada kalimat ‘kita’ adalah bagian dari anak nagari tanpa membedakan etnis.
Penulis adalah Jaringan PSIK-Paramadina untuk Demokrasi dan Islam

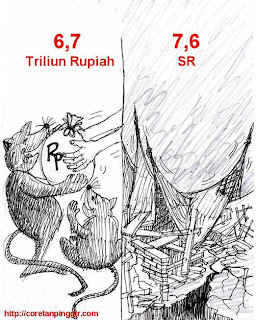
Komentar